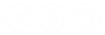“My momma always said , ‘Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get’.” Apa jadinya ketika yang kamu temukan adalah bom?
Seorang perempuan mendapat selembar tiket penerbangan gratis, entah dari siapa. Pertemuannya dengan seorang kritikus musik diatas langit mengembalikannya pada memori tentang mantan pacarnya. Apa yang terjadi selanjutnya ternyata menghantamnya kembali ke tanah.
Sekuens prolog diatas menjadi pembuka dari Wild Tales, sebuah anthological thriller yang membawa penonton ke dalam fantasi liar manusia: egomaniacal vengeance, satu yang tidak dimiliki oleh jenis makhluk hidup bumi lainnya. Berisikan enam cerita, masing-masing premis mampu mengkonstruksi makna kata ‘dendam’ dengan caranya yang serupa: ‘kekerasan’. Kecelakaan, perdebatan, perkelahian, frustasi, hingga pengkhianatan, semuanya menjadi tinta untuk menorehkan kata ‘dendam’, layaknya ‘kematian’ menjadi cantus firmus dari film-film Jidai-Geki era ’50-an.
Paruh pertama antologi membangun dua tema besar tersebut dengan caranya yang terbilang menggelitik, jika tidak ingin dibilang hilarious. Penonton seolah diingatkan kembali dengan film-film Coen Brothers yang menciptakan unsur komediknya secara gelap. Sesi ‘Pasternak’ menggunakan ketidaksengajaan sebagai subjek awal untuk mencetak kepuasan hasrat dendamnya. ‘The Rats’ (‘Las Ratas‘), disisi lain, mencampurkan secuil debat moral klise ditengah satirisme sosial tentang baik-buruknya mengotori tangan sendiri demi membalas dendam. ‘Road To Hell’ (‘El mas fuerte‘), sesi terakhir dari babak pertama, menjadi klimaks dengan menggabungkan gritty violence ala Quentin Tarantino dan dark humour Takeshi Kitano secara padat ditengah lanskap rural highway dan perkelahian dua pria yang menggelikan.
Di paruh keduanya, Wild Tales sedikit mengendurkan injakan gas humornya dengan lebih menitikberatkan unsur satirisme nyinyir dan tragedi yang ironik. Disini, penonton dikembalikan lagi pada makna ‘dendam’ dan ‘kekerasan’ dalam metafora umumnya: sebuah bom waktu yang siap meledak kapanpun. Di sesi keempat, ‘Bombita‘, penonton dikenalkan pada Simon Fischer, seorang demolition expert yang mendapati dirinya terjebak dalam lingkaran setan birokrasi korup yang nyaris menghancurkan kehidupan pribadinya. Disini bom waktu secara harafiah dipakai sebagai objek pemuasan tendensi dendam sekaligus menertawakan kondisi sosial manusia yang koruptif. Tema korupsi sendiri secara kontras dihadirkan pada ‘The Deal’ (‘La Propuesta‘), sesi keempat, dimana sebuah keluarga yang mapan berusaha menyelamatkan anaknya dari insiden tabrak lari yang dilakukannya. Dengan lebih tebalnya unsur tragedi pada ‘The Deal’, kata ‘dendam’ hanya menjadi letupan ringan namun mengagetkan di akhir sesi.
‘Until Death Do Us Part’ (‘Hasta que la muerte nos separe‘), sesi terakhir dari Wild Tales, menjadi sekuens pamuncak yang berhasil mengaduk berbagai warna yang disajikan di sesi-sesi sebelumnya. Dimulai dari ironi yang ditampilkan dalam suasana resepsi pernikahan megah namun menyimpan sumbu dinamit ketika Romina, sang mempelai perempuan, menemukan fakta tentang Ariel, suaminya, dan salah satu tamu wanita di pernikahannya sendiri. Ledakan yang ditampilkan pun tidak tanggung-tanggung, semuanya katastrophik dan berakhir secara absurd.
Revenge is a dish best served cold. Namun di Wild Tales, dendam jauh lebih nikmat bila disantap panas, layaknya secangkir kopi pahit yang bisa mendebarkan jantung ketika diseruput selagi hangat.
***
Wild Tales (Relatos Salvajes) diputar oleh Komunitas Layar Tancep Parahyangan (KLTP) dalam perayaan soft-opening Sorge Coffee yang bertempat di CO-OP Space, Aula Gedung UKM Unpar, pada hari Senin, 29 Juni 2015.