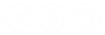Saya lahir tanggal 22 Desember 1988, bertepatan dengan tanggal digelarnya Kongres Perempuan Indonesia pertama 60 tahun silam. Orang tua saya sangat bangga akan hal itu, maka diberinamalah saya Sri Andhini. Walau tak persis betul momentumnya, ayah saya memberi nama anak pertamanya ini dengan kata “Sri”. Ia mengambilnya dari salah satu tokoh perempuan yang mendeklarasikan perjuangannya atas nama kemanusiaan, Sri Mangoensarkoro. Mereka berharap saya seberani Beliau dalam bercakap dan bersikap. Dengan begitu berarti nama asli saya hanya Andhini, tanpa Sri.
Sejak kecil saya selalu ditimpa kesialan-kesialan. Kata ibu, kesialan itu dimulai sejak saya lahir. Ketika melahirkan saya, keluarga kami sangat kekurangan biaya sehingga harus banyak berhutang pada tetangga. Tragisnya pada perjalanan menuju rumah sakit ayah saya dirampok, ludeslah uang pinjaman itu. Sri Andhini kecil terpaksa ditahan di rumah sakit beberapa hari sebagai jaminan, hingga akhirnya ayah dapat melunasi biaya bersalin. Diam-diam saya bersyukur mereka tidak menamai saya Sri Prihatini karena sangat memprihatinkannya kondisi kami pada itu. Bayangkan, kalau sampai Sri Prihatini. Artinya saya tidak punya nama asli.
Kejang
Kata nenek, Sri Andhini kecil selalu tampak menyenangkan jika sedang makan. Apa pun yang keluarga sajikan, saya pasti melahapnya dengan penuh gairah. Tentu saya tumbuh menjadi anak yang sehat lagi gemuk menggemaskan. Tak seorang pun menyangka anak sesehat saya dapat sakit, sampai suatu hari saya terjatuh di depan teras. Kejang-kejang. Di usia tiga tahun saya.
Tanpa pikir panjang ibu membawa Sri Andhini kecil ke unit gawat darurat, tentunya bersama tetangga-tetangga baik hati yang siap mendanai tindakan sementara. Menurut dokter, sumsum tulang belakang saya harus diambil. Ibu menangis tak karuan. Ia tahu, kemungkinan saya hidup normal setelahnya sangat kecil. Lagi pula pengambilan cairan sumsum tulang belakang adalah proses medis yang sangat menyakitkan. Tak jadilah saya melalui prosesi menyakitkan itu. Ibu memilih ambil resiko membiarkan kejang-kejang itu dapat terulang kembali.
Beruntung sakit saya tak masuk level sangat parah. Seminggu kemudian saya diperkenankan pulang. Saya kembali jadi Sri Andhini yang sehat walafiat. Tentu saja keadaan keluarga kami tidak ikut sehat. Ayah dan ibu terpaksa menghutang kembali, kali ini dengan sistem gadai. Sayang beberapa perhiasan ibu tak kembali karena kami tak sanggup melunasi.
Patah Tulang
Sri Andhini tumbuh menjadi perempuan yang gemar main pedang-pedangan. Ayah sepertinya terobsesi memiliki anak lelaki. Dari tiga kardus mainan yang ada di rumah, hanya satu yang berisi barbie, selebihnya robot-robotan atau pistol-pistolan. Pada usia
enam tahun saya mendapatkan sepeda pertama beroda tiga. Hanya butuh tiga minggu bagi Sri Andhini kecil untuk lancar menungganginya, beranilah saya untuk melepas dua roda bantuannya.
Bersepada di sore hari menjadi ritus yang sama wajibnya dengan solat Jumat bagi anak lelaki di kompleks kami. Sejak dibelikan sepeda, saya pun tak pernah absen berkenalan. Saya paling cantik diantara lainnya. Saya bangga bersepeda merah, walau harus memakai rok kemana-mana. Kata ibu hanya itu yang membedakan saya dengan anak lelaki, menyedihkan.
Suatu hari, saya terlalu bersemangat mengayuh pedal hingga rantainya terlepas. Ketika Sri Andhini kecil sedang panik menginjak rem, sebuah mobil melaju kencang dari arah turunan depan kompleks. Tabrakan tak terelakan. Saya terlempar tiga empat meter ke depan. Beruntung saya jatuh menubruk pagar tetangga, bukan selokan. Merasa harus tetap keren, berdirilah saya dengan segera. Kawan-kawan lelaki berteriak histeris. Kaki saya bengkok!
Sakit baru terasa setelah menyadarinya. Beruntung ahli parah tulang di Kalimalang sukses menyulap kaki dengan apik. Dalam tiga bulan kaki saya telah normal kembali. Saya tetap bersepeda, namun kini ibu mengizinkan saya bercelana panjang. Rok tidak selalu aman, dalihnya.
Tersiram Air Panas
Gemar bermain dengan anak lelaki tidak membuat saya alpa tugas sebagai anak perempuan. Tiap jam lima sore, sepulang bersepeda saya selalu membantu ibu menyiapkan makan malam di dapur. Ayah akan tiba jam enam dan saat itu di atas meja makan sudah harus tersedia setidaknya teh manis dan setanggap roti untuknya. Ritual memasak di sore hari mengajarkan saya untuk selalu memberi perlakuan khusus para lelaki. Ayah selalu mendapat sendok, garpu dan piring terbaik dari lemari kami. Mereka juga harus didahulukan masalah makan, termasuk dapat makanan yang enak (kelak saya tahu itu konstruksi bodoh, setelah pacar saya membentak ketika saya bermaksud memberikannya segala yang terbaik soal perintilan makan).
Waktu itu usia saya sembilan tahun. Mpok Ipeh, tenaga ahli baru di rumah kami, sedang membuat mie goreng di dapur. Seperti biasa, saya menjalankan ritual sore. Kelar bersih-bersih sepulang bersepeda, saya menghampirinya dan berdiri persis di sebelahnya. Mpok Ipeh sudah tua, mungkin 50-an usianya, jadi wajar ia tidak mendengar langkah kaki saya. Di sebelah kanan kompor ada bak cuci piring. Tak terlalu besar memang, namun jaraknya dekat dengan kompor. Saya masih berdiri persis di samping kanan Mpok Ipeh. Tiba-tiba… Byuuuuurrrrr!!! Tumpahlah air mendidih berisi mie di dalam panci. Mpok Ipeh baru bermaksud tiriskan airnya, tapi tak menyadari keberadaan saya di sampingnya. Jadilah ia tak sengaja wajah saya tersiram air mendidih.
Saya tak ingat apa rasanya. Yang saya ingat sepertinya saya berteriak dan ibu berlarian dari ruang keluarga ke dapur. Ingatan saya tidak pada rasa sakitnya yang pasti luarbiasa, tapi bagaimana reaksi ibu saat itu. Ia membopong saya dengan tangan bergetar hebat. Ia menangis kencang, mungkin wajah saya terlihat begitu menyedihkan sehingga pantas ditangisi sebegitu hebatnya. Saya ingat ibu berteriak panik menelepon ayah, beri kabar berita. Setelah itu hilang. Saya tak ingat satu apa pun.
Yang saya tahu, tiga bulan kemudian wajah saya kembali normal karena rajin diolesi salep untuk luka bakar. Normal dalam artian tidak meninggalkan bekas tersiram air panas sedikit pun, sebuah keberuntungan. Yang saya ingat, Mpok Ipeh tetap bekerja di rumah kami untuk waktu yang cukup panjang setelahnya. Yang saya sadari, hingga saat ini saya agak takut ke dapur. Saya takut bersentuhan dengan api, minyak, apa lagi air mendidih.
Bola Basket
Ayah dan ibu mulai menyadari siklus kesialan saya yang berputar tiap tiga tahun sekali. Mereka harap-harap cemas tiap jelang tahun ketiga setelah kesialan terakhir. Orang tua Sri Andhini punya tabungan khusus untuk berjaga-jaga. Tentu saja saya frustasi
menjelang tahun ketiga. Tiap detik adalah satu peluang hangat jatuhnya saya pada kesialan musiman tersebut. Pesakitan.
Syukurlah pada tahun ke-12 saya tak terjadi kesialan yang cukup berarti, hanya murni—menurut saya—kebodohan. Saat itu pelajaran olahraga, yang perempuan diminta menonton anak-anak lelaki tanding basket. Saya duduk di samping kiri ring basket karena di sanalah tempat paling teduh di lapangan. Semua bersorak memberi semangat pada Reno, si jagoan basket SMP kami. Ya, dia memang keren, tapi menyorakinya histeris hanya membuat kami tampak bodoh memuja lelaki.
Tibalah saat ia melempar bola sekuat tenaga. Bola basket itu melesat dari tengah lapangan ke arah ring basket. Meleset. Bola itu tepat mengenai wajah saya! Persis di wajah perempuan berkacamata. Setelah terkena serangan, saya hanya tertawa sambil melepas kacamata, sakit memang tapi saya merasa tidak apa-apa. Kawan-kawan berteriak histeris (semacam deja vu).
Rupanya hidung saya berdarah. Bingkai kacamata saya yang terbuat dari besi agaknya sempat tertancap pada tulang hidung saya. Secuil daging tipis menempel di kacamata waktu saya melepasnya. Reno sangat menyesal. Ia minta maaf berkali-kali pada saya dan
sebagian fans-nya melirik tajam ke arah saya yang saat itu banjir darah dari hidung.
Ah ya. Tahun ke-12 saya agak beruntung hanya itu yang terjadi. Murni kebodohan si Reno dan saya yang duduk mencari teduh. Kejadian itu membuat saya tak lagi pernah membeli bingkai kacamata berbahan besi. Saya juga agak mengurangi sentuhan dengan benda berbentuk bola. Keduanya tampak beresiko.
TBC
Sebuah keajaiban terjadi. Tahun ke-15 saya lalui tanpa satu pun kesialan serius atau bodoh sekali pun. Saya melalui masa remaja dengan tenang, setidaknya untuk tiga tahun mendatang. Sri Andhini mulai jadi remaja kota metropolitan. Mulai berpacaran, berciuman dan pulang menjelang malam.
Kelas saya berada di lantai empat. Tak ada tangga jalan menuju kelas, yang ada hanya anak tangga dengan hantu perempuan bermukim di lantai dua dan tiga. Lambat laun saya merasa tak kuat menaiki tangga dan mengikuti pelajaran olahraga. Diam-diam saya merasa ada yang tidak beres dengan tubuh saya. Mustahil, kalau pun sakit pasti tidak mungkin diluar siklus tiga tahunan itu, batin saya.
Akhirnya, Sri Andhini berulang tahun ke-17. Kawan-kawan datang ke rumah, mengejar, menangkap dan menghujani saya dengan lemparan telur ayam juga tepung terigu. Saya diarak sampai depan teras dan digosok dengan sikat baju pada seluruh tubuh, dimandikan secara paksa. Keesokan harinya saya tidak masuk. Batuk luarbiasa hebat menjelang malam. Keringat bercucuran tanpa ampun.
Hasil rontgent keluar. Paru-paru saya berkabut. Putih dengan bercak abu di beberapa titiknya, membentuk lubang. Batuk saya mulai dihiasi darah kental berwarna merah tua. Saya makin tak kuat menaiki tangga dan mulai berhenti mengikuti pelajaran olahraga. Hasil cek dahak menunjukan saya positif TBC, penyakit para perokok. TBC seharusnya bukan penyakit perempuan yang hobi berpacaran, berciuman dan pulang menjelang malam seperti saya. Dokter memvonis saya hanya mampu bertahan tak lebih dari tiga tahun bermain di dunia, ia minta saya rajin minum obat. Rutin. Enam bulan lamanya. Hancur sudah hidup saya!
Saya berhenti berpacaran, berciuman dan pulang menjelang malam. Tak ada satu pun yang tahu saya TBC. Itu penyakit menular. Kata ibu, tak ada yang mau main dengan saya jika mereka tahu. Dimulailah hari-hari paling menyakitkan dalam hidup saya. Terbangun
di tengah malam karena rusuk terasa menusuk organ-organ yang ia lindungi. Berteriak di tengah malam karena kedua kaki kram dan sakit bukan main. Keringetan sekaligus kedinginan hebat di tengah malam. Saya menangis tiap tengah malam. Saya takut mati
dan ragu mau bunuh diri.
Saya berhenti mengkonsumsi “obat kuat” itu pada bulan ke-4 masa pengobatan. Alasannya sederhana, kalau pun saya harus mati kenapa harus menunda kematian. Bodoh memang, tapi obat hanya membuat saya merasa lemah. Bayangkan saja, saya harus menelan tujuh butir obat berbagai warna dan ukuran tiap harinya, nyaris tiga kali sehari. Bagaimana tidak melemahkan? Itu adalah kali pertama saya tertimpa kesialan di luar lingkar siklus sial tahunan. Dan mungkin TBC jadi kesialan yang paling sial dalam hidup saya. Ia mengubah segalanya.
Saya jadi harus menghindari kegiatan fisik yang terlalu berat, seperti orang lemah. Saya selalu membuat orang cemas tiap kali diajak pergi jauh. Mereka selalu takut tiba-tiba saya merasa sesak kemudian menangis dan marah karena kesal. Dikasihani itu lebih melemahkan bagi saya. Ya. TBC mengubah saya tak hanya jadi lemah, tapi juga bodoh dalam melawan Tuhan, saya mulai merokok, walau hanya satu dua batang kalau sedang ingin atau kesal.
Tubuh
Nama saya Sri Andhini. Setiap tiga tahun sekali, saya selalu tertimpa masalah besar berupa kesialan yang menyakitkan. Orang tua saya telah menyiapkan tabungan khusus untuk itu.
Saya lahir tanggal 22 Desember 1988. Persis pada hari dideklarasikannya suara perempuan dalam sejarah perpolitikan bangsa lewat Kongres Perempuan Indonesia pertama 60 tahun sebelumnya. Meski tak persis betul momentumnya, orang tua saya ingin anaknya berani dalam bercakap juga bersikap, seperti Sri Mangoensarkoro yang tatkala itu mengatakan pergerakan perempuan lahir di atas nilai kemanusiaan.
Di usia 20 tahun saya mulai mengenal persetubuhan. Tentunya persetubuhan yang bertanggung jawab, dalam artian memang di luar pernikahan dan tidak suka pakai kondom tapi saya tidak pernah bergonta-ganti pasangan.
Di usia 20 tahun saya mulai mengenal tubuh saya. Mengenal luka yang ada padanya. Saya juga mulai mengenal kesedihan padanya. Sebuah keterkungkungan dalam tubuh perempuan ini, terlebih pada tubuh yang tiap tiga tahunnya tertimpa satu kesialan bodoh.
Saya mulai menggeser pola olahraga ringan saya dengan persetubuhan yang hangat. Keintiman yang tak terbeli, walau tak selalu menyenangkan karena beberapa kali saya selalu menangis tiap kali dada mulai merasa sesak kehabisan udara. Persetubuhan membawa saya pada sebuah kenyamanan dan khayalan purba masa kanak-kanak. Khayalan yang kau dapatkan pada masa oral, kenikmatan pada ibu jari dalam mulutmu. Di sisi lain persetubuhan mendorong saya pada jurang kekecewaan dan ketakutan akan keperempuanan saya. Saya.. Apa masih layak disebut perempuan?
Memasuki bulan-bulan akhir tahun ketiga kesialan—dihitung dari terakhir saya mendapat kesialan, yakni usia 17 tahun—saya merasa tenang. Entahlah. Apa gerangan yang Tuhan ingin tunjukan melalui rasa sakit di tubuh saya. Rasanya sudah cukup. Ia pun sukses membuat saya dua kali mencoba bunuh diri. Keduanya dengan melukai nadi. Tentu saja gagal. Saya tak cukup berani. Saya benci merasa lemah dan dikasihani jika tak benar mati.
Suatu malam menjelang ulang tahun saya ke-21, ada rindu dan resah. Saya mengajak bersetubuh pasangan monogami saya, lelaki yang diam-diam bermimpi poligami suatu hari nanti.
Pada suatu titik permainan kami saya merasa ingin orgasme. Diburu nafsu dengan bodohnya. Seakan mengejar ketinggalan kereta, saja berpacu. Dada saya mulai terbakar, panas. Otot saya mulai mengencang. Pengelihatan saya mulai kabur. Tubuh saya mulai bergetar, mengejar. Kemudian pada satu titik semua itu buyar. Saya kehilangan nafas. Jantung saja berhenti tiga empat hitungan. Saya terjatuh dan menangis sekencang-kencangnya. Itulah momentum paling mengerikan dalam hidup saya. Bukan karena nyaris mencapai garis finish, lebih kepada itulah garis kehidupan saya nyaris tergunting. Saya bertemu Tuhan lewat nikmat, sakit dan ketakutan membuncah di satu momentum yang sama.
Saya
Siklus kesialan tiga tahunan saya berhenti sampai di situ. Ditutup tidak dengan kesialan, namun dengan sebuah pelajaran. Bukan tubuh yang pantas merasa berdosa atas luka yang menderanya. Saya hanya butuh merasa tidak lemah dalam kebertubuhan saya, karena tubuh hanya ilusi yang penuh ketakutan semu. Saya masih punya ruh. Ruh yang berhutang pada tubuh di 40 hari sebelum peniupannya. Orang tua saya tidak pernah tahu pada momentum apa saya terakhir kali berjumpa dengan kesialan tahunan itu. Tentu saja saya tak mau dan tak akan menceritakannya. Bercerita sama saja dengan menyembelih leher sendiri.
Saya hanya menyampaikan pada mereka bahwa saya ingin memiliki nama sendiri. Nama yang saya pilihkan untuk diri saya. Tak harus mengganti keseluruhannya, cukup menambahkan satu kata di belakang kata terakhir. Saya lahir pada 22 Desember 1988. Orang tua saya berharap saya menjadi perempuan yang berani dalam bercakap dan bersikap. Saya pun juga berharap sama, oleh karena itu saya memutuskan untuk jadi penulis. Saya menulis dengan tubuh. Saya menulis tentang kebertubuhan dan keperempuanan saya.
…
“Halo! Perkenalkan, nama saya Sri Andhini Larasati. Kamu?”
Wara Aninditari Larascintya Habsari adalah mahasiswi jurusan Kriminologi Universitas Indonesia dan Alumni Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) Kontras 2013.