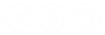Video ini adalah volume pertama dari dokumentasi video diskusi “Tanah Jakarta Milik Siapa?” yang diselenggarakan Forum Diskusi Jakarta (FDJ) dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jumat (11/10). Dalam video ini, Jo Santoso (Pengajar Studi Perkotaan Universitas Tarumanegara) memaparkan bagaimana perubahan tata ruang di Jakarta, dan bagaimana hal itu bisa terjadi.
Latar Belakang Diskusi “Tanah Jakarta Milik Siapa?”
Jika anda ialah pekerja Jakarta yang bergaji sedikit di atas Upah Minimum Regional), sebaiknya lupakan cita-cita untuk memiliki rumah atau apartemen luas di kota ini. Begitulah kira-kira pesan tersembunyi dari berbagai iklan properti di televisi oleh para pengembang besar. Dengan memasang sejumlah biaya yang mungkin tak akan pernah ada di buku tabungan kita, sudah tentu yang dituju dari iklan tersebut bukanlah kebanyakan kelas menengah Jakarta apalagi yang lebih miskin. Jika yang tergolong berpendapatan tinggi di Jakarta hanya 20% dari total penduduk, apakah memang tanah di Jakarta tidak diperuntukan untuk sebagian besar warganya?
Banyaknya permintaan di Jakarta sebagai pusat perekonomian menjadi alasan untuk pengembang untuk terus mengerek harga. Namun anehnya, logika pasar yang sama tak berlaku ketika kebanyakan warga Jakarta tak mampu lagi membeli. Dengan ketidakmampuan menjangkau biaya itu, seharusnya harga pasar pun menyesuaikan dengan daya beli kebanyakan orang. Tapi dalam pandangan tunggal bahwa memupuk modal sebanyak-banyaknya adalah lumrah, daya beli mayoritas tak lagi jadi acuan.
Kini banyak kaum berpunya membeli sebidang tanah dan bangunan tak lagi didasarkan pada kebutuhan untuk tempat tinggal atau membangun usaha. Pembelian properti telah beralih menjadi fungsi menjadi sarana investasi. Artinya seseorang memiliki lebih banyak properti dari yang dia butuhkan sebagai tempat tinggal atau usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan berlipat. Inilah salah satu penyebab banyaknya kamar apartemen yang kosong meski dibilang pengembang sudah terjual habis. Selain itu, gejala serupa di kota-kota besar seluruh dunia dimana banyak rumah-rumah tak berpenghuni meski banyak pula tunawisma juga mengafirmasi hal tersebut.
Akumulasi properti untuk investasi yang membuat harga melambung mendorong kelas pekerja untuk mencari hunian di tempat yang jauh dari pusat kota atau di luar Jakarta. Bagi masyarakat yang lebih miskin, menempati hunian-hunian “illegal” tak terhindarkan. Kawasan kumuh yang dibangun di area non pemukiman pun bermunculan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kota melakukan hal yang tipikal: penggusuran atas nama hukum dan ketertiban. Sesuatu yang ramai kita dapati di Jakarta akhir-akhir ini.
Penggusuran kawasan kumuh dan pembangunan kawasan yang dianggap lebih tertib dan bersih juga mendorong harga tanah dan properti di kawasan itu menjadi tinggi. Hal yang biasa disebut gentrifikasi ini makin membuat warga kota berpendapatan rendah menjadi makin kehilangan akses pemukiman. Bagi kelas menengah, para pengusaha properti masih menawarkan hunian di area pinggiran kota. Ini berarti kabar buruk bagi lingkungan penyangga kota: akan lebih banyak tanah yang dibuka dan makin sedikit serapan air.
Data tahun 2015 menyebutkan bahwa 42% pendapatan warga dipakai untuk menyicil rumah atau membayar sewa. Tren ini terus meningkat dan menjadi bukti jelas bahwa kian lama tanah dan bangunan di ibukota makin susah terakses warga miskin dan kelas menengah. Dari sekian banyak persoalan di ibu kota, harga tanah melangit nampaknya lebih diterima sebagai hal yang normal daripada problem lain seperti kemacetan dan banjir. Padahal, investasi rakus di sektor properti ini lah yang juga menyebabkan krisis di Amerika dan Eropa pada tahun 2008. Belum lagi dengan gentrifikasi jurang perbedaan antara mereka yang berpunya dan tak berpunya menjadi makin kentara. Tidak dipungkiri, properti dan tanah yang tak sanggup terbeli di Jakarta menyisakan bom waktu tersendiri.